Saat itu umur Ma’e masih 4 tahun. Untuk kali pertama yahwa Suman membawa Ma’e kecil ke meunasah melaksanakan shalat maghrib. Tak banyak jama’ah yang datang, hanya beberapa orang-orang tua kampung, selebihnya anak-anak yang berlari kesana-kemari waktu shalat tiba.
Semenjak itu Ma’e mulai berkenalan dengan meunasah. bagi anak-anak seusia Ma’e, meunasah telah menjadi tempat baru untuk bermain, kejar-kejaran atau apalah namanya, terkadang juga menjadi tempat bagi para orang tua melepas penat.
Jama’ah paling banyak adalah ketika maghrib tiba, kemudian ‘isya disusul jamaah shubuh yang terdiri dari beberapa orang tua saja. Ketika sore hari perkarangan meunasah yang sedikit luas berubah menjadi arena main bola. Tepat di belakang meunasah mengalir sebuah lueng kecil yang digunakan anak-anak untuk mandi ria.
“Suram masa depan Meunasah nye lagee nyoe, jama’ah hana sagai...” kata syik Nu, sang imum meunasah suatu kali, sambil menghirup rokok on-nya diatas bale. Tapi Syiek Nu tidak lagi bersusah payah memikirkan tentang bangunan meunasah. Karena tampang meunasah sudah berubah jauh.
Bangunan Meunasah sudah cukup megah bercat putih. meunasah tampak berdiri gagah karena bantuan pemerintah setahun lalu. Tapi sayang seribu sayang, gagahnya meunasah tidak segagah jama’ah yang datang. Ia sepi, hanya ada beberapa orang tua saja yang tak sanggup lagi menggerakkan suara. “si ge treuek ta greuhem eureueng syiek nyan, sang langsung meuninggai geueh…” celutuk Bram (aslinya Ibrahim) seorang preman kampung suatu kali.
Kemana anak muda? Anak-anak muda bangai seperti Ibrahim tadi sibuk dengan ibadah mereka. Tak ada tanda-tanda berubah sama sekali pada meunasah. Karena memang tak ada yang membuat perubahan.
Tahun-tahun terus berlalu tanpa bisa dicegah, pertanda bumi semakin tua. Ma’e telah tumbuh dewasa, ia telah menyelesaikan sarjananya di Universitas Unsyiah jurusan tehnik sipil, ia juga telah bekerja pada sebuah NGO bersama orang-orang bulek, rekan kerjanya memanggilnya Mr Ismail, nama yang begitu asing di kampungnya dulu. Asing karena belasan tahun hidup di kampung tercinta, tak ada satu orangpun memanggil Ma’e dengan Ismail, kecuali almarhumah syik Ramlah dulu, syiek Ma’e tercinta.
Meunasah Ma’e tetap saja tidak berubah bahkan lebih menyedihkan. “meunasah tak ada lagi imam, imamnya sudah tak kuat karena uzur. Beliau memilih beristirahat, hanya sesekali ke meunasah…”. Kata anak-anak suatu kali pada Ma’e.
Anak muda? Sekali lagi mereka masih saja beribadah dengan dunianya. Tak peduli meunasah itu, meunasah yang dipertahankan bertahun-tahun lamanya oleh para indatu. Anak-anak masih saja berlari kesana-kemari. Air di lueng meunasah sudah kering, mungkin tak ada lagi berkat yang tersisa. Dulu digunakan untuk berwudhuk tapi entah karena sering digunakan untuk mandi dan buang hajat, maka jadinya seperti itu.
“Allahu Akbar…Allahu Akbar…”, anak-anak berhenti bermain, eureueng jak u blang berhenti mencangkul, dan mak-mak di rumah berhenti seumeupeh. Sejenak mendengar kumandang azan merdu dari meunasah, siapa gerangan? Ma’e telah mengambil alih semuanya, menjadi Imum meunasah. Lebih dari itu, ia telah meninggalkan pekerjaannya pada NGO. Demi meunasah, warisan indatu. Demi agama!
Angin terus berhembus dingin, itek-itek plati terlihat berkumpul kompak. Awan–awan putih berarak rapi, kemudian mengumpal membentuk sketsa. perlahan hujan mulai turun membasahi meunasah dan jama’ah. Waktu ashar telah tiba, teungku Ma’e masih disana!
Jum’at yang berkah, Cairo 12 Nov ‘10
Pukul 9:44 PM
Semenjak itu Ma’e mulai berkenalan dengan meunasah. bagi anak-anak seusia Ma’e, meunasah telah menjadi tempat baru untuk bermain, kejar-kejaran atau apalah namanya, terkadang juga menjadi tempat bagi para orang tua melepas penat.
Jama’ah paling banyak adalah ketika maghrib tiba, kemudian ‘isya disusul jamaah shubuh yang terdiri dari beberapa orang tua saja. Ketika sore hari perkarangan meunasah yang sedikit luas berubah menjadi arena main bola. Tepat di belakang meunasah mengalir sebuah lueng kecil yang digunakan anak-anak untuk mandi ria.
“Suram masa depan Meunasah nye lagee nyoe, jama’ah hana sagai...” kata syik Nu, sang imum meunasah suatu kali, sambil menghirup rokok on-nya diatas bale. Tapi Syiek Nu tidak lagi bersusah payah memikirkan tentang bangunan meunasah. Karena tampang meunasah sudah berubah jauh.
Bangunan Meunasah sudah cukup megah bercat putih. meunasah tampak berdiri gagah karena bantuan pemerintah setahun lalu. Tapi sayang seribu sayang, gagahnya meunasah tidak segagah jama’ah yang datang. Ia sepi, hanya ada beberapa orang tua saja yang tak sanggup lagi menggerakkan suara. “si ge treuek ta greuhem eureueng syiek nyan, sang langsung meuninggai geueh…” celutuk Bram (aslinya Ibrahim) seorang preman kampung suatu kali.
Kemana anak muda? Anak-anak muda bangai seperti Ibrahim tadi sibuk dengan ibadah mereka. Tak ada tanda-tanda berubah sama sekali pada meunasah. Karena memang tak ada yang membuat perubahan.
Tahun-tahun terus berlalu tanpa bisa dicegah, pertanda bumi semakin tua. Ma’e telah tumbuh dewasa, ia telah menyelesaikan sarjananya di Universitas Unsyiah jurusan tehnik sipil, ia juga telah bekerja pada sebuah NGO bersama orang-orang bulek, rekan kerjanya memanggilnya Mr Ismail, nama yang begitu asing di kampungnya dulu. Asing karena belasan tahun hidup di kampung tercinta, tak ada satu orangpun memanggil Ma’e dengan Ismail, kecuali almarhumah syik Ramlah dulu, syiek Ma’e tercinta.
Meunasah Ma’e tetap saja tidak berubah bahkan lebih menyedihkan. “meunasah tak ada lagi imam, imamnya sudah tak kuat karena uzur. Beliau memilih beristirahat, hanya sesekali ke meunasah…”. Kata anak-anak suatu kali pada Ma’e.
Anak muda? Sekali lagi mereka masih saja beribadah dengan dunianya. Tak peduli meunasah itu, meunasah yang dipertahankan bertahun-tahun lamanya oleh para indatu. Anak-anak masih saja berlari kesana-kemari. Air di lueng meunasah sudah kering, mungkin tak ada lagi berkat yang tersisa. Dulu digunakan untuk berwudhuk tapi entah karena sering digunakan untuk mandi dan buang hajat, maka jadinya seperti itu.
“Allahu Akbar…Allahu Akbar…”, anak-anak berhenti bermain, eureueng jak u blang berhenti mencangkul, dan mak-mak di rumah berhenti seumeupeh. Sejenak mendengar kumandang azan merdu dari meunasah, siapa gerangan? Ma’e telah mengambil alih semuanya, menjadi Imum meunasah. Lebih dari itu, ia telah meninggalkan pekerjaannya pada NGO. Demi meunasah, warisan indatu. Demi agama!
Angin terus berhembus dingin, itek-itek plati terlihat berkumpul kompak. Awan–awan putih berarak rapi, kemudian mengumpal membentuk sketsa. perlahan hujan mulai turun membasahi meunasah dan jama’ah. Waktu ashar telah tiba, teungku Ma’e masih disana!
Jum’at yang berkah, Cairo 12 Nov ‘10
Pukul 9:44 PM


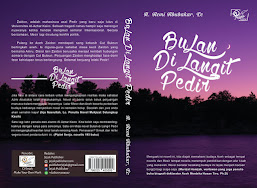
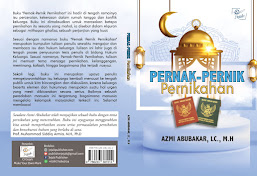

0 Komentar